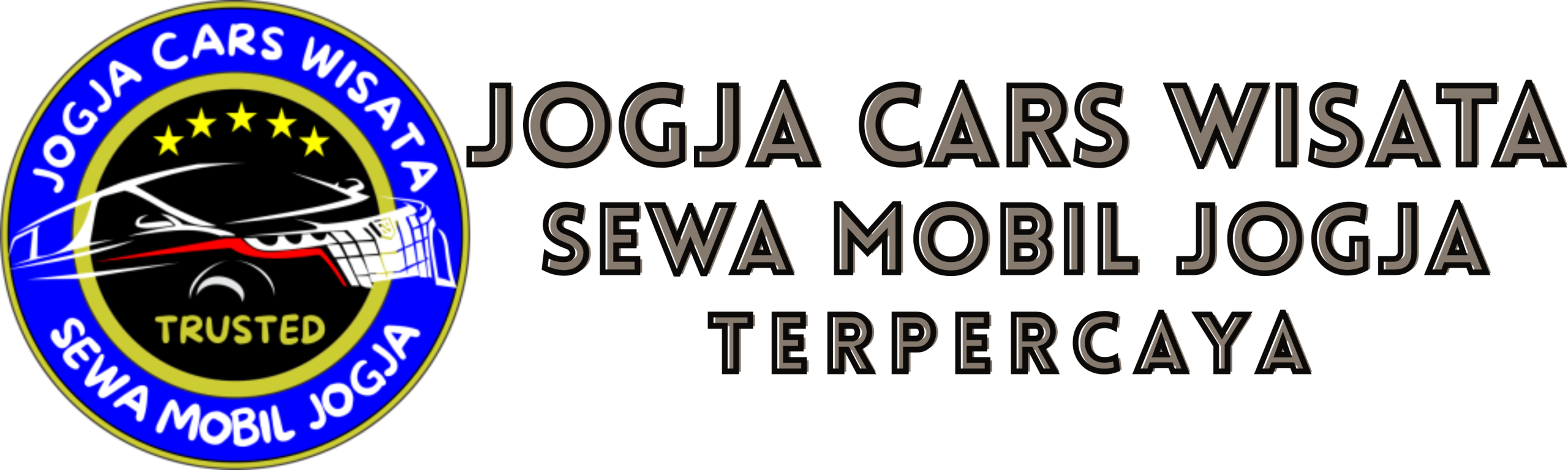Keberadaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang memegang kekuasaan tertinggi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan sejarah makam Raja-raja Mataram di Imogiri. Makam Raja-raja Mataram di Imogiri menjadi saksi bisu atas kejayaan Kerajaan Mataram di masa lampau hingga puncak kejayaannya dan membagi dua wilayah Kerajaan Mataram melalui perjanjian Giyanti.
Perjanjian Giyanti
Dalam perjanjian Giyanti Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua yakni Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I (HB I) dan Kasunan Surakarta yang dipimpin oleh Pangeran Pakubuwana III. Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tanggal 13 februari 1755 M. Dinamakan perjanjian Giyanti karena lokasi perjanjian ini bertempat di Desa Giyanti atau sekarang menjadi Dukuh Kerten, Desa Jatiharjo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar.
Wilayah Kasultanan Yogyakarta meliputi sebagian besar Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Sedangkan wilayah Kasunan Surakarta meliputi sebagian besar wilayah Solo Raya yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen.

Wilayah Kasultanan Yogyakarta menjadi provinsi tersendiri yakni Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi beda halnya dengan wilayah Kasunan Surakarta yang seluruh wilayahnya masuk kedalam provinsi Jawa Tengah.
Lokasi Makam Raja – Raja Mataram Islam
Makam Imogiri atau Pasarean Imogiri merupakan tempat peristirahatan terakhir Raja – Raja Mataram beserta dengan keluarganya. Kompleks pemakaman ini secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Girirejo dan Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak dari Keraton Yogyakarta sekitar 16 km ke arah selatan atau waktu tempuh 30 menit menggunakan kendaraan roda empat.
Pemilihan Bukit Imogiri Sebagai Makam Raja Mataram Islam
Pemilihan bukit Imogiri sebagai tempat pemakaman Raja – Raja Mataram beserta keluarganya bukan tanpa sebab. Namun karena lokasi yang menjadi makam Raja – Raja Mataram di Imogiri saat ini cukup dekat dengan komplek Istana Kerajaan Mataram Islam Kotagede (1588 – 1613 M).
Kotagede merupakan Ibukota Kerajaan Mataram Islam yang didirikan Panembahan Senopati. Sisa peninggalan komplek Istana Kerajaan Mataram Islam Kotagede masih bisa dijumpai hingga saat ini seperti Masjid Gedhe Mataram, Makam Raja – Raja Mataram Kotagede, pasar Kotagede, serta bangunan-bangunan peninggalan lainnya.
Bukit sebagai lokasi makam tidak dapat dilepaskan dari konsep masyarakat Jawa pra Hindu yang memandang bukit atau tempat yang tinggi, sebagai suatu tempat yang sakral. Dengan lokasinya yang berada di perbukitan tentu harga keranda mayat dibuat khusus agar memudahkan pembawa keranda mayat membawa keranda mayat dengan aman hingga tujuan. Apalagi ketiga menaiki tangga makam Imogiri yang cukup panjang.

Disisi lain, pemilihan lokasi bukit di Imogiri karena nama Imogiri berasal dari kata “Hima” dan “Giri”. “Hima” berarti kabut dan “Giri” berarti gunung, sehingga Imogiri bisa diartikan sebagai gunung yang diselimuti kabut. Gunung yang diselimuti kabut menimbulkan hawa dingin sehingga saat para Peziarah mengunjungi makam Raja – Raja Imogiri maka akan merasakan hawa sejuk atau dingin.
Sejarah dan Arsitektur Makam Imogiri
Makam Imogiri atau Pasarean Imogiri dibangun pertama kali pada tahun 1632 M, ketika masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613 – 1645 M). Kala itu pembangunan makan dilakukan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma beserta keluarga dan jajarannya yang dipimpin oleh Kyai Tumenggung Citro Kusumo.
Sultan Agung Hanyakrakusuma menjadi Raja pertama yang dimakamkan di makam Imogiri beserta Istri, anak, dan keluarganya serta Kyai Tumenggung Citro Kusumo. Pembangunan kompleks makam Imogiri kala itu dengan arsitektur makam perpaduan antara Hindu dan Islam. Area makam Imogiri didominasi dengan bata merah pada bagian atas yang merupakan ciri utama desain arsitektur Rumah Islam Jawa atau arsitektur Islam Hindu pada abad ke – 17.
Batu bata yang menyusun area bangunan Makam Imogiri tidak direkatkan dengan menggunakan semen atau perekat sejenisnya namun batu bata tersebut disusun dengan metode gosok. Dimana permukaan atas batu bata yang berada di bagian bawah digosokkan dengan permukaan bawah batu bata yang berada di bagian bawah, kemudian diberi sedikit air hingga keluar semacam cairan pekat. Cairan pekat inilah yang kemudian melekatkan satu batu bata dengan batu bata lainnya sehingga membentuk komplek makam.

Dalam komplek makam Imogiri terdapat garis anak tangga dengan posisi antar gapura menuju pemakaman, dari bawah hingga ke atas membentuk sebuah garis lurus. Gapura-gapura tersebut menjadi batas wilayah bagi area-area dalam pemakaman.
Raja-Raja Mataram Islam yang Disemayamkan di Makam Imogiri
Tidak semua Raja – Raja Mataram Islam dikuburkan di makam Imogiri. Raja yang pertama kali disemayamkan di makam Imogiri adalah Sultan Agung Hanyakrakusuma sekaligus sebagai pencetus pembangunan makam Imogiri. Pemakaman ini kemudian digunakan oleh Raja – Raja penerusnya, bahkan ketika Kerajaan Mataram dibagi menjadi 2 wilayah kekuasaan yakni Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
Pembagian kerajaan ini kemudian turut membagi wilayah pemakaman Imogiri. Saat ini makam Imogiri terdiri dari beberapa komplek utama yakni Kasultanagungan, Pakubuwanan, Kasunanan Surakarta, dan Kasultanan Yogyakarta.
Makam Imogiri atau Pasarean Imogiri menjadi saksi bisu kejayaan dan pasang surut Kerajaan Mataram Islam serta Kerajaan – kerajaan penerusnya. Walaupun Ibukota kerajaan melakukan perpindahan lokasi berkali-kali hingga kerajaan terbagi menjadi 2 wilayah. Akan tetapi Raja-Raja tersebut tetap berpulang pada satu tempat peristirahatan terakhir. Kebesaran nama dan kisah perjuangan mereka terpahat di puncak Makam Imogiri.